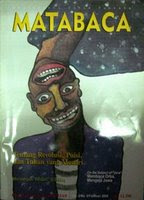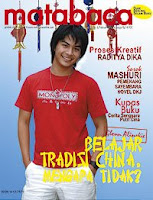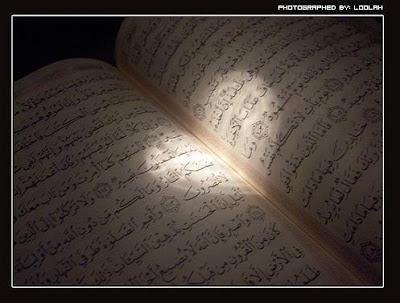 “Ya Allah, seandainya kiamat kelak Kau hisab aku, jangan lakukan itu di samping Rasul Musthafa. Aku malu telah mengaku umatnya, padahal hidupku bergelimang dosa.”
“Ya Allah, seandainya kiamat kelak Kau hisab aku, jangan lakukan itu di samping Rasul Musthafa. Aku malu telah mengaku umatnya, padahal hidupku bergelimang dosa.”SETIAP MENGENANG atau membaca kembali sejarah hidup seseorang, kita selalu dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa banyak hal dari orang tersebut yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita tuai dalam menjalani hidup kita. Itulah sebabnya barangkali sejarah hidup seseorang dinamakan biografi, yang secara harfiah berarti “gambar hidup”.
Begitupun ketika kita mengenang kembali kehidupan Rasulullah Saw. Di masyarakat Melayu, memperingati kelahiran dan hidup Nabi Muhammad selalu disertai ritus pembacaan kitab Barzanji, biografi Nabi Muhammad yang dikarang oleh seorang ulama bernama Al-Barzanji. Di Yogyakarta, menjelang peringatan maulid Nabi, diadakan karnaval budaya bernama sekaten. Dua contoh ini menarik. Kalau akhir-akhir ini banyak orang mengusulkan tentang pembacaan Alquran lewat tradisi yang hidup di masyarakat, yang disebut dengan living Quran (Alquran yang hidup), tradisi perayaan maulid untuk mengenang sejarah hidup Muhammad tak lain adalah bentuk sejarah yang hidup, tak sekadar sejarah hidup.
Pertanyaannya, mengapa sejarah Nabi terus hidup, mengapa ada upaya-upaya yang bahkan telah mentradisi untuk menghidupkannya? Jawabannya tidak lain sebab kita teramat mencintai Nabi akhir zaman itu. Perayaan maulid adalah upaya mengenang Nabi secara periodik.
Kenangan dan ajaran Nabi itu terus hidup karena sejarah Nabi, di dalam Islam, menjadi pedoman atau sumber ajaran Islam. Sunnah atau hadis yang kita kenal tidak lain merupakan sejarah Nabi. Sunnah juga, di dalam Islam, menjadi penafsir Alquran yang paling otoritatif. Antara Alquran dan perilaku Nabi memang sulit dipisahkan. Di dalam sebuah hadis disebutkan, “Akhlak Nabi adalah Alquran.” Almarhum Fazlur Rahman di dalam bukunya Islam menyebutkan bahwa sejarah hidup Nabi merupakan bukti aktual Alquran di dalam sejarah.
Kalau demikian, sejarah Nabi yang paling tepat dan benar, sesungguhnya cukup dibaca di dalam Alquran. Memang, alih-alih detail, Alquran hanya memberi gambaran sedikit tentang sifat Nabi. Kata Alquran di dalam
Di dalam buku biografinya, baik yang ditulis oleh sarjana muslim seperti Husain Haikal (Hayatu Muhammad, diterjemahkan Penerbit Litera Antarnusa Jakarta dalam bahasa Indonesia menjadi Sejarah Hidup Muhammad), maupun oleh orang nonmuslim seperti Karen Armstrong (Muhammad: A Biography of the Prophet, diterjemahkan Mizan Bandung menjadi Muhammad Sang Nabi), kedua sifat itu secara detail dijabarkan. Bagaimana solidernya Nabi terhadap kaumnya, secara jelas dapat dilihat kala hijrah. Sewaktu akan hijrah, Nabi menyuruh para sahabatnya untuk berangkat terlebih dahulu ke Yastrib atau Madinah. Dia sendiri bersama Abubakar berangkat belakangan. Saat Nabi tiba, para sahabatnya yang telah terlebih dahulu pergi, menyambutnya. Kejadian itu tidak semata strategi di saat kritis, bagaimana bisa keluar dari Mekkah saat kaum kafir Quraisy sedang mengepung, tapi juga sebentuk solidaritas: bahwa dirinyalah yang menyediakan diri atas segala risiko yang dihadapi dalam hijrah.
Di lain kesempatan, saat perang, Nabi memimpin dengan turun langsung ke
Pelajaran solidaritas ini dalam banyak hal berbanding terbalik dengan keadaan pemimpin kita saat ini. Siapa yang mau solider dengan penderitaan rakyat yang semakin bertambah-tambah akibat ekonomi yang terus memburuk? Bahkan, saat rakyat kekurangan pangan, harga bahan makanan melambung, para pemimpin berencana menganggarkan uang negara untuk membeli fasilitas mereka (membeli laptop atau jalan-jalan ke luar negeri dengan dalih studi banding, misalnya).
Nabi sangat solider. Di samping solider, dia juga amat kasih pada yang beriman. Karena sifat-sifatnya itu, Nabi dicintai kaumnya, termasuk kita. Bagi kita umat belakangan, yang tidak bertemu Nabi, bukti kecintaan itu antara lain diwujudkan dengan kita yang berharap bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Nabi bersabda, “Barangsiapa melihatku di dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku.”
Berbagai ritual pun dilakukan agar bisa bertemu Nabi dalam mimpi. Antara lain berwudhu sebelum tidur, membaca beberapa
Sulit memang mencari siapa sekarang yang mencintai Nabi seperti itu. Di dalam sejarah, kala Nabi hidup, ada kisah tentang kecintaan itu. Di sebuah musim haji, Nabi berpidato untuk yang terakhir kalinya. Inilah peristiwa yang disebut haji wada’ atau haji perpisahan dengan Nabi. Nabi berpidato meminta maaf kepada kaumnya. Bila ada yang merasa pernah dijahati Nabi, silakan membalas atau men-qishash. Seorang sahabat berdiri dan bilang, saat dia berperang, tubuhnya pernah tercambuk oleh Nabi. Tercambuk, bukan dicambuk. Nabi pun menyuruh Ali mengambil cambuknya. Nabi telah bersiap untuk dicambuk, tapi sahabat itu tetap urung. Dia bilang, saat tercambuk Nabi, punggungnya sedang terbuka. Nabi pun membuka pakaiannya. Saat orang menahan napas, tak tega dengan pembalasan itu, bahkan Umar sempat menawarkan agar punggungnya saja yang dicambuk sebagai ganti, dan ini ditolak Nabi, sahabat yang siap mencambuk tiba-tiba melempar cambuk dan memeluk serta menciumi Nabi sambil berkata, “Aku rindu untuk menempelkan punggungku dengan punggungmu, Ya Rasulullah.” Rasulullah merasa haru dan bilang, “Inilah ahli surga.”
Itu cermin orang yang mencintai Nabi, yang pernah mencium Nabi. Tapi siapakah yang pernah dicium oleh Muhammad Rasulullah?
Setidaknya ada dua orang. Pertama adalah Fatimah, putri bungsu beliau. Sebagaimana semua orang, anak adalah buah kasih sayang tiada terperi. Anak adalah tumpuan cinta, sekaligus harapan. Begitu juga Nabi. Dengan anak-anaknya beliau sangat penyayang. Dan yang paling disayangi di antara putri-putrinya adalah Fatimah. Entah mengapa Fatimah. Bisa jadi karena dia bungsu, sebagaimana kebanyakan orang punya rasa sayang berlebih pada si bungsu ketimbang kakak-kakaknya. Kalau demikian, apakah Nabi kurang adil terhadap anak-anaknya? Tidak bisa dinilai demikian. Justru, sifat inilah yang memperlihatkan kepada kita betapa Muhammad adalah juga manusia. Dan kasih sayang pada anak bungsu yang berlebih adalah hal yang sangat manusiawi. Kata Alquran, “Telah datang kepadamu Rasul dari kalian sendiri.” “Dari kalian sendiri” kata sebagian tafsir adalah rasul bangsa manusia, punya sifat manusiawi, bukan utusan berbentuk malaikat, misalnya.
Namun ada juga pendapat, Nabi teramat mencintai Fatimah sebab tahu bahwa garis keturunannya akan terus bersambung lewat Fatimah, tidak saudara-saudaranya yang lain. Dan kenyataan dalam sejarah memang demikian. Bagi kaum Syiah, ini sering kali dianggap dalil keunggulan Ali dan keturunannya lewat Fatimah, sehingga membuat mereka memuliakan keluarga ini (ahlul bayt).
Terlepas dari itu, yang jelas Nabi sangat menyayangi Fatimah. Bentuk kasih sayang itu antara lain ditunjukkan Nabi dengan sering memangku Fatimah sewaktu kecil, bermain-main dengannya. Konon, Fatimah berlari-lari kecil dan Nabi menyambut dalam pelukannya. Di situ Nabi kemudian dengan gemas menciumi tangan Fatimah yang mungil. Bentuk kasih sayang orangtua yang sangat wajar. Dan Fatimah, setidaknya, adalah seorang yang pernah dicium Nabi.
Kedua, di dalam sebuah riwayat dikatakan, Nabi sedang duduk di masjid bersama para sahabat. Namun di antara sahabat itu ada yang tampak menyembunyikan tangannya. Nabi dapat menangkap gelagat itu. Nabi lantas bertanya ada apa dengan tangan itu. Sahabat tersebut menjawab, tangannya rusak, ber-kapal. Mengapa rusak, tanya Nabi. Jawab sahabat itu, sebab dia membanting tulang bekerja kasar untuk menghidupi keluarganya. Demi mendengar jawaban tersebut, Nabi lantas mengambil tangan sahabat itu lalu menciuminya sambil bersabda, “Inilah tangan yang mulia, tangan ahli surga.”
Membaca kisah ini hari ini, kita pantas tersindir. Adakah pemimpin yang sudi mencium tangan rakyatnya? Lihatlah, di pinggir-pinggir jalan, di perempatan lampu merah, betapa banyak anak-anak dan pengemis menghiba meminta sebagian rizki. Mereka tak punya apa-apa. Mereka bekerja jauh lebih kasar dari yang diduga: menghamba meminta-minta adalah perbuatan yang lebih menyakitkan ketimbang kerja kasar apa pun. Dan itu sudi dikerjakan mereka, demi menghidupi keluarga, demi anak-anak kecil mereka yang mungkin tengah sakit atau telah beberapa hari tak memeroleh asupan susu. Dan, adakah pemimpin kita saat ini yang mau meraih tangan mereka, menciumi tangan buruk mereka? Kita bisa menduga, tak ada. Bahkan lewat pun, dengan kendaraan mewah lengkap pengawal, para pemimpin itu tak sempat barangkali melongok kaca melihatnya. Ataukah mereka sengaja tak mau melihatnya?
Mencium tangan kaum papa sesungguhnya adalah metafora bahwa kaum papa harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Bila mereka tetap ada di negeri ini, tak memeroleh garansi hidup, itu sama artinya kita tak meneladani Nabi yang sudi memuliakan kaum tak berpunya.
================
* Tulisan ini saya buat dengan referensi ingatan semata. Mohon kroscek ulang bila ingin mengutip, terutama menyangkut nama, ayat, dan hadis.